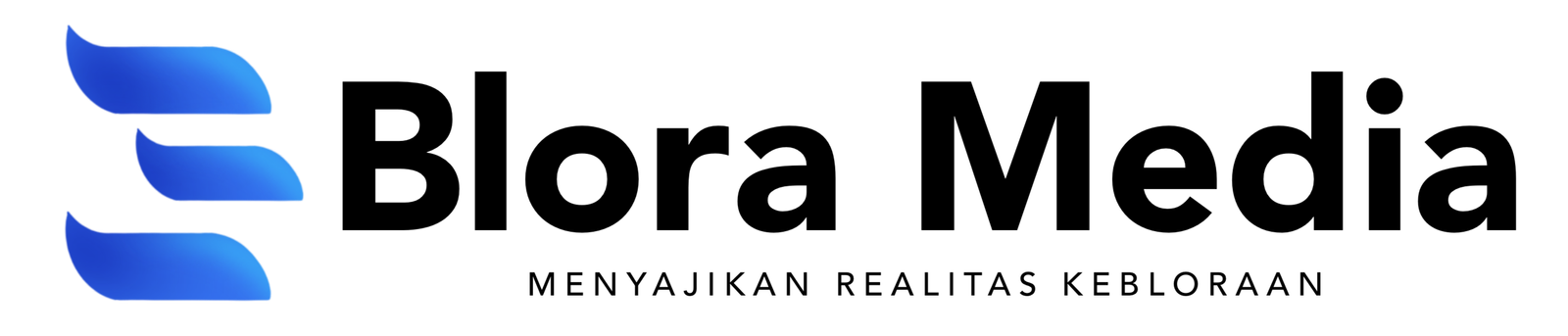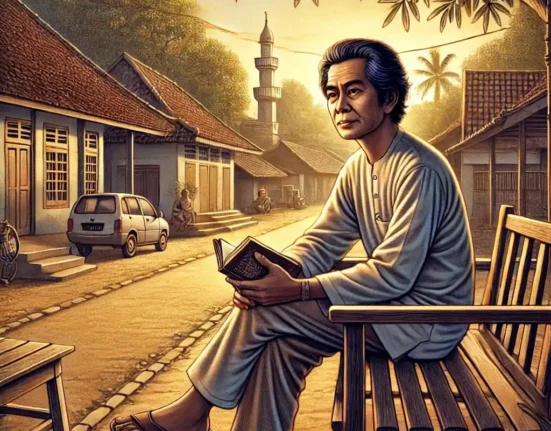Kabupaten Blora, yang hampir separohnya dikelilingi perbukitan dan hutan yang tumbuh subur, dengan luas mencapai 40%, selama ini telah menghasilkan sumberdaya yang menyimpan keuntungan dan aset yang sangat besar. Namun sayang, pundi-pundi keuntungan itu tak pernah tersentuh sampai ke tangan kita, nahasnya bahkan sering merugikan sebagian masyarakat. Perhutani terlibat dalam pengolahan dan pengelolaan terhadap hutan dan kebun-kebun yang mereka kendalikan.
Tiap tahunnya, seluruh hutan yang dikelola Perhutani di Indonesia mampu mendulang untung hingga 3,927 triliun pada 2020, lalu naik target menjadi 7 triliun pada 2022 dari pengolahan 1,4 juta hektare lahan yang ditanami berbagai jenis pohon dan segala jenis yang bisa diolah di hutan. Program hilirisasi, yang sebetulnya berdampak terhadap ekosistem flora dan fauna lewat pembalakan dan reduksi lahan telah berubah menjadi kontrol sistem yang sulit dibendung. Akibatnya terjadi reduksi lahan dari yang semula 2,4 juta hektare dapat dikelola Perhutani, sekarang berkurang menjadi 1,4 juta hektare.
Kawasan yang menjadi sentra pengelolaan Perhutani ini umumnya merupakan wilayah-wilayah pedesaan dan perbukitan yang tersebar di seluruh titik Indonesia. Setiap administrasi mempunyai karakter ekosistem tumbuhan masing-masing. Di Jawa pada umumnya hutan-hutan Perhutani ditanami pohon jati, sonokeling, randu dan tebu. Jika kontur tanahnya lebih lembab, pohon seperti pinus dan karet juga dikelola dan diolah oleh Perhutani. Untuk pengawasannya, mereka memiliki kantor-kantor yang tersebar di setiap KPH, mempunyai tiga kantor induk divisi regional di tiga provinsi, memiliki pusat pendidikan dan pengembangan pegawai di Madiun, dan pusat penelitian dan pengembangan kehutanan yang berada di Cepu, Blora.
Perhutani merupakan lembaga dagang milik BUMN, berdiri sejak tahun 1961. Pada awalnya merupakan sebuah perusahaan Jawatan Kehutanan yang dibentuk pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1897. Basis wilayahnya berada di sepanjang hutan Jawa dan Madura, yang 21% wilayahnya merupakan area hutan dan kebun jati. Saat itu, pemerintah Hindia-Belanda telah menerapkan program reboisasi dan penebangan hasil alam atas seluruh wilayah Jawatan Kehutanan untuk dapat diolah dan diperdagangkan. Seluruh hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan diserahkan kepada kepala Jawatan Kehutanan–pada umumnya ialah seorang lelaki yang berasal dari Belanda, yang dengan pengalamannya berhasil membuat beberapa kantor besar, baik induk ataupun cabang, untuk mengirim hasil hutan dengan didorong juru langsir dengan kereta lori dan membawa glondong-glondong kayu itu ke tapal pelabuhan untuk nantinya diangkut dan diarung kapal laut menuju Benua Eropa dan dijual. Salah satu produk unggulan Jawatan Kehutanan pada masa itu adalah industri kayu jati, yang banyak tumbuh di pedalaman hutan Jawa dan Madura. Dibanding jati yang tumbuh di Myanmar atau Thailand, jati yang tumbuh di Jawa lebih diakui kualitasnya karena pengaruh tanah dan keawetannya. Ketangguhan pohon jati dari Indonesia, khususnya yang berasal dari pedalaman hutan Jawa di Blora telah mendapat pengakuan dari bangsa-bangsa Eropa sebagai tempat produk jati paling kesohor. Karena pohon tectona grandis (jati berukuran besar) adalah yang paling awet dan mahal, Jawatan Kehutanan pada saat itu menetapkan hutan Randublatung di Blora yang awalnya woud afdeeling (hutan kabupaten) berubah status menjadi houtvesterijen (hutan milik Belanda). Maka dari sini, pemerintah Belanda dengan bebas bisa menjual produk jati Jawa ke Eropa dengan harga yang sangat mahal tanpa gangguan dan belenggu dari citra dagangnya yang terkenal korup dan lintah penghisap itu.
Ade Rosalina, dalam skripsinya yang berjudul Analisis dan Pengaruh Komoditas Ekspor Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Blora, yang dipublikasi oleh Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (tahun 2017). Ia menyebut; “Afdeeling Blora adalah salah satu daerah utama penghasil kayu jati berkualitas terbaik di Indonesia.”
Benih pohon jati, selain merupakan produk lokal, umumnya merupakan impor yang didatangkan dari Afrika Selatan. Setiap tahun, antara Mei sampai Agustus, akan dipersiapkan penanaman benih baru, dan bibit jati itu akan mulai tumbuh ketika memasuki musim hujan di bulan September sampai November. Benih ditanam dalam kedalaman 1 meter, biasanya dalam 1 lubang bisa berisi tiga benih sekaligus. Benih lalu ditekan ke tanah, lalu ditandai dengan tongkat, prosesnya hampir mirip seperti menanam bibit ketela dan jagung. Bila perawatannya bagus, tinggi pohon jati bisa 10 meter lebih, karena memiliki lebih banyak asupan gizi dari tanah yang lebih padat. Sementara pohon yang tidak memenuhi syarat akan ditebang, sehingga menyisakan jarak yang lebih besar untuk pohon yang masih bercokol di sampingnya. Seorang perawat yang tekun biasanya akan mulai mengurangi jumlah pohon dan menyadap tubuh jati, dan ini diulangi sampai umur pohon mencapai 60 atau 70 tahun. Namun dari 15 pohon yang ditanam, biasanya hanya muncul satu yang berkualitas terbaik.
Kayu jati di Jawa memiliki nilai yang luhur. Di era kerajaan sampai bercokolnya beberapa keraton Islam, kayu jati digunakan sebagai bahan utama pembuatan pilar-pilar bangunan penting, seperti masjid, pendopo dan bangunan inti istana. Kayu jati digunakan sebagai selingan batu kapur dan andesit yang sering diambil dari sungai-sungai purba. Selain itu, semakin besar pohon jati yang dapat ditebang, maka semakin sakral pula nilainya. Di dalam Serat Centhini yang disusun oleh Pakubuwono V, ia mengulik bahwa kayu jati memiliki watak atau sifat yang dapat mempengaruhi penghuninya, dan tak jarang kayu jati dengan ukuran yang sangat besar ditempatkan di beberapa tempat yang dianggap masyarakat memiliki nilai sakral. Umumnya pohon jati mulai layak dipanen bila sudah mencapai umur antara 80 sampai 100 tahun, maka tak ayal pohon jati menjadi buruan di komoditas perdagangan dengan harga yang sangat mahal. Dan hanya orang-orang tertentu yang sanggup membeli dan memilikinya. Bahkan masyarakat Jawa pada zaman dulu menganggap rumah-rumah keluarga yang diisi perabot dan bahan material dari kayu jati akan dipandang memiliki status sosial yang tinggi.
Terlepas dari pandangan masyarakat Jawa. Pada saat itu Jawatan Kehutanan menganggap kayu jati cocok untuk diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan pokok sebuah bangunan. Kayu-kayu jati berkualitas terbaik akan dibawa ke pabrik penggergajian dan dipotong-potong sesuai ukuran. Waktu itu, kayu jati telah dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan gerbong trem dan umpak jalur kereta api. Selain itu, kayu jati juga diolah menjadi bahan baku pembuatan badan jembatan, yang memerlukan bilah-bilah papan jati yang kuat dan awet. Di industri mebel, kayu jati diolah menjadi bahan utama pembuatan perabot, yang diedarkan mindring oleh kuli-kuli pengangkut. Dan yang paling utama, hampir seluruh penduduk di Jawa pada waktu itu menggunakan kayu jati sebagai bahan pokok bangunan, sehingga pembalakan dan penebangan hutan jati di daerah Jawa terus-menerus diadakan untuk mencukupi kebutuhan manusia dan industri modern.
Karena kekayaan alam dan sumber daya inilah, Jawatan Kehutanan sempat direbut oleh militer Jepang saat masa pendudukan singkat selama 3 tiga tahun. Jepang melakukan penebangan besar-besaran untuk kebutuhan perang di Asia Pasifik, terutama untuk bahan bangunan barak, kamp, dan bahan bakar kereta api. Karena ditebang dan dibongkar secara asal-asalan, akibatnya terjadi deforestasi dan erosi, dan hujan tropis mulai menyapu pasir kering dari sungai ke hulu laut, jika hujan deras mulai turun, seringkali permukiman yang dekat dengan hutan ikut tersapu banjir.
Namun kemudian Belanda kembali mengeksploitasi seluruh hutan Jawa saat mereka kembali setelah tahun ’45. Dalam pengolahan yang singkat itu, kayu-kayu jati kembali diangkut dan dijual ke Eropa, dan tetap menjadi komoditas unggulan sebagai bahan utama bangunan. Setelah Belanda menyerah, dan Indonesia merdeka, seluruh hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan diserahkan kepada pemerintah Indonesia, untuk disempurnakan dan didirikan kembali pada tahun 1961. Atau tepatnya 62 tahun yang lalu.
Memang, eksploitasi dari Belanda telah berhenti, namun tidak dengan sumberdaya dan alamnya. Setiap tahun terjadi pembalakan dan penebangan, baik penebangan liar yang dicurigai dikerjakan oleh kelompok blandong, atau penebangan resmi yang dilakukan Perhutani. Jumlah-jumlah kubik kayu terus berkurang setiap tahunnya, walaupun ada alibi penghijauan dan reboisasi, namun pohon jati perlu proses yang sangat panjang untuk selalu bertahan hidup. Lahan-lahan konservasi semakin lama semakin berkurang, dan kontur tanahnya semakin lama semakin hancur dan buruk.
Karena lahan di hutan Perhutani sebagian besar tidak bisa diolah oleh penduduk, sebagian besar masyarakat yang hidup di pinggiran hutan hidup dalam kemiskinan yang paling akut. Ini telah terjadi sejak era kolonial Belanda mulai mengerjakan orang-orang yang hidup di sekitar hutan jati sebagai buruh bergaji rendah. Mereka para lelaki pada umumnya akan berangkat ke hutan membawa kerbau dan sapi mereka. Dengan diawasi seorang mandor kepala, para buruh yang bermodalkan sangkur, parang, gergaji dan perkul ini akan mulai memanjat pohon jati, kemudian menebangnya perlahan-lahan sampai pohon itu rubuh. Setelahnya, untuk sampai di pabrik penggergajian, mereka menggunakan tenaga kerbau dan sapi mereka untuk menyeret kayu-kayu yang belum dipotong itu ke stasiun lori, yang berada di tepi hutan, dibuat khusus sebagai jalur angkutan kayu-kayu menuju tempat pengolahan. Bayangkan saja, tenaga mereka dikuras, hewan ternak mereka dipakai, dan seluruh sumberdaya di wilayah mereka dikeruk dan dieksekusi oleh akademi Belanda yang kotor dan tamak itu. Para buruh ini dilarang mencuri sumberdaya yang ada di dalam hutan, termasuk kayu jati itu, sebab status hutan rakyat yang telah diklaim menjadi hutan milik Belanda. Sementara para pencuri-pencuri kecil ini, oleh orang Belanda sering disebut sebagai blandong, kumpulan suku kecil di Jawa yang karena tak digaji layak oleh Belanda, memaksa mereka untuk mengambil hasil alam yang sebenarnya berhak mereka miliki. Inilah yang kemudian diteliti oleh geografer Amerika bernama Nancy Lee Peluso, yang dengan tegas menyebut desa-desa di tengah hutan jati Jawa adalah desa-desa termiskin di antara yang miskin.
Peluso menyebut hutan-hutan rakyat yang sekarang diklaim sebagai hutan politis (political forest) adalah salah satu cara perampasan hutan rakyat yang paling kontroversial. Pola-pola perampasan tanah rakyat menjadi tanah milik negara ini sudah dimulai sejak zaman Belanda, dan sistemnya kembali digunakan bahkan setelah Indonesia merdeka. Sehingga orang kemudian menganggap bahwa sistem Perhutani, terkait perampasan hutan rakyat, peraturan dan kontrol secara ketat, sering disebut sebagai Belanda model baru. Maka tak heran bila muncul para blandong kayu jati, sebab mereka adalah bagian yang keluar dan yang berani memberontak dari mekanisme hutan politis, yang sering kita dengar ceritanya;
“Ada seorang polisi hutan menembak teman ngopinya di warung setelah ia ketahuan blandong kayu di hutan…”
Tak ada yang membantah bahwa mayoritas penduduk pinggiran di hutan Jawa hidup dalam keterbatasan dan melarat. Mereka biasanya hanya mendapat jatah tanah yang jauh lebih kecil untuk ditanami ketela dan jagung, bila musim hujan tiba, tanah sewaan itu dibajak dan mulai ditanami padi. Mereka ini dinamakan petani pesanggem. Kadang-kadang mereka mengolah hasil hutan itu dengan cuma-cuma, tetapi sering juga mereka datang ke pos tertentu untuk mengirim upeti dan sejumlah uang, sebagai ganti atas lahan yang telah penduduk garap selama ini.
Kasus seperti ini masih ada, anda yakin Belanda masih jauh?