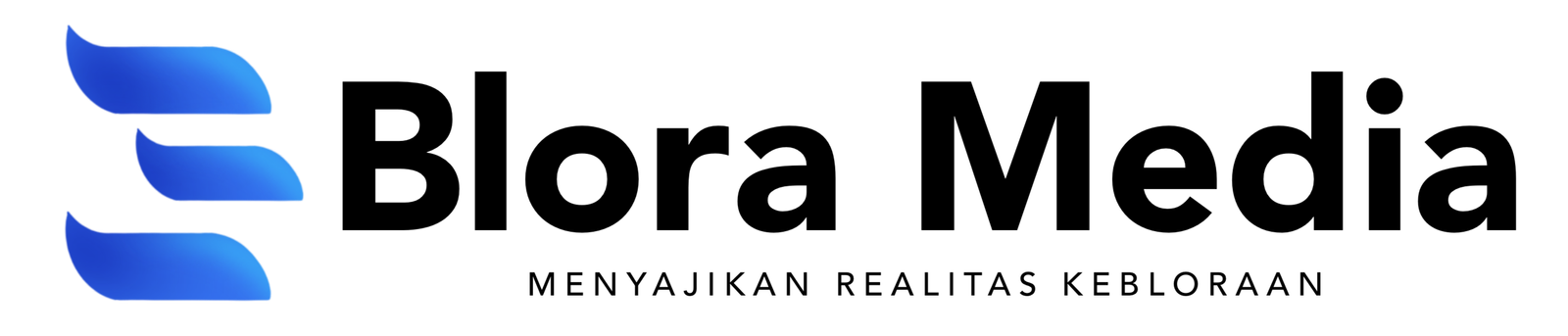Aku masih ingat dengan jelas hari pertama ketika kakiku menginjakkan diri di Desa Sambongrejo. Sebuah desa sederhana di Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, yang kelak akan memberiku kenangan seumur hidup. Jalanan berdebu menyambut kedatangan kami, rombongan mahasiswa KKN dari kampus IAI Khozinatul ulum blora. Langkah kami penuh semangat, meski dalam hati ada sedikit gugup—bagaimana kehidupan di sini? Bagaimana kami bisa diterima masyarakat? Dan bagaimana nanti rasanya harus meninggalkan desa ini setelah 45 hari?
Rumah sederhana dengan teras luas di pinggir jalan tengah desa menjadi posko kami. Di sanalah aku pertama kali bertemu dengan sosok yang akan kukenang sepanjang hidupku: Mbahe. Seorang perempuan tua dengan wajah teduh dan senyum yang tak pernah hilang. Tangannya keriput, tubuhnya mulai bongkok, tapi semangat melayani tamunya luar biasa. Ia menyambut kami dengan ramah, “Monggo, Le, mlebu. Iki omahmu dhewe. Ora usah sungkan-sungkan.” Ucapan itu membuatku merasa seperti pulang ke rumah sendiri.
Sejak hari pertama, aku dan teman-teman KKN merasa nyaman di rumah itu. Setiap pagi, ketika matahari belum sepenuhnya naik, Mbahe selalu menyiapkan teh hangat di meja ruang tamu. “Wis tak gawekna teh, Le, ngombe dhisik ben semangat,” katanya sambil tersenyum. Teh manis dalam gelas kaca sederhana itu entah kenapa rasanya berbeda—ada kehangatan, ada kasih sayang yang tulus. Teh yang membuat kami betah bercengkerama sebelum berangkat menjalani aktivitas.
Namun, sebelum teh itu kuminum, aku punya kebiasaan yang tak pernah kutinggalkan. Setiap pagi, aku berjalan menuju masjid yang berada tak jauh dari posko. Udara subuh di Sambongrejo begitu khas; dingin, segar, bercampur aroma tanah basah. Suara kokok ayam bersahutan, sesekali kucing mengeong dari kejauhan. Di tengah sunyi itu, aku melangkah ke masjid, mengumandangkan azan subuh. “Allahu Akbar… Allahu Akbar…” Suaraku menggema, menyatu dengan keheningan desa.
Setelah azan, kami shalat berjamaah dengan imam masjid, Bapak Huda. Beliau adalah sosok yang begitu karismatik, suara bacaannya lembut, penuh ketenangan. Yang membuatku tertegun, setiap kali aku berdiri di belakangnya, aku merasa seperti kembali menjadi makmum di mushola kampungku sendiri, ketika almarhum ayah masih hidup. Ayahku dulu juga seorang imam mushola, suaranya tegas tapi penuh kasih, gerakannya khusyuk. Kini, bertahun-tahun setelah ayah pergi, aku menemukan bayangannya di diri Bapak Huda. Entah kenapa setiap kali aku sujud di belakang beliau, mataku terasa panas, air mataku nyaris jatuh. Seakan-akan aku kembali dipeluk doa ayah dari surga.
Hari-hari KKN pun bergulir. Pagi kami habiskan dengan mengajar anak-anak di SD Negeri 1 Sambongrejo. Wajah-wajah polos itu menyambut kami dengan antusias. “Pak Yusron, kapan ngajar maneh?” tanya seorang anak bernama Rian dengan mata berbinar. Aku hanya tersenyum, “Besok, insyaAllah kita belajar lagi.” Mengajar mereka bukan hanya soal membaca dan berhitung, tapi juga soal belajar bermimpi. Aku ingin mereka tahu, meski tinggal di desa, mereka punya kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.
Sore hari, aku dan beberapa teman mengajar di TPQ. Suara anak-anak melantunkan ayat Al-Qur’an membuat suasana sore selalu syahdu. Kadang kami tertawa ketika ada yang salah membaca, tapi segera memperbaikinya dengan sabar. Malamnya, kami ikut kegiatan tahlilan atau yasinan bersama warga. Kehidupan desa begitu hangat, penuh kebersamaan. Tak ada yang merasa asing; semua seperti keluarga.
Di posko, Mbahe selalu menjadi pusat perhatian kami. Ia sering duduk di teras sambil menunggu kami pulang. “Wis bali, Le? Ngantuk ora? Sarapanen sing akeh, awake kudu sehat,” katanya setiap kami terlihat lelah. Kadang ia ikut mendengarkan cerita-cerita kami, meski tak selalu mengerti isi obrolan mahasiswa. Senyumnya saja sudah cukup membuat kami bahagia. Ia seperti ibu, nenek, sekaligus penjaga hati kami selama di Sambongrejo.
Waktu berjalan cepat. Rasanya baru kemarin kami datang dengan koper besar, kini sudah mendekati hari-hari terakhir. Aku mulai merasakan kegelisahan. Setiap kali azan subuh di masjid, aku berpikir: sebentar lagi aku tak akan lagi berdiri di mimbar itu, tak akan lagi mendengar lantunan lembut Bapak Huda yang mengingatkanku pada ayah. Setiap kali meneguk teh hangat buatan Mbahe, aku sadar: sebentar lagi meja ruang tamu itu tak akan lagi dipenuhi gelas kaca untuk kami.
Hari terakhir KKN tiba dengan cepat. Pagi itu, Mbahe sudah menyiapkan teh lebih banyak dari biasanya. “Iki terakhir aku nggawe teh kanggo kowe kabeh, Le,” katanya dengan suara bergetar. Aku menahan air mata. Gelas itu kupegang erat, seakan-akan dengan meneguknya aku bisa menyimpan kenangan 45 hari di Sambongrejo. Teh itu bukan sekadar minuman, tapi simbol cinta yang tak tergantikan.
Setelah sarapan, kami berkumpul di posko untuk pamitan. anak-anak berlari menghampiri kami. Rian memeluk kaki kak haris erat-erat, “kak haris ojo lunga. Ngajarke aku meneh.” Aku terdiam, hatiku perih. Aku berjongkok, menatap matanya, “Aku harus pulang, Rian. Tapi kamu janji ya, terus belajar. Jangan pernah berhenti.” Anak itu mengangguk sambil menangis.
Shalat subuh terakhir bersama Bapak Huda juga tak akan pernah kulupakan. Suaranya sama, gerakannya sama, tapi aku tahu ini terakhir kalinya aku sujud di belakangnya. Setelah salam, aku tak mampu menahan tangis. “Pak, jenengan koyo bapak kula dhewe,” kataku terbata. Beliau menepuk pundakku lembut, “InsyaAllah, doa bapakmu terus nyertai kowe, Le. Terusno perjuanganmu.” Kata-kata itu menancap dalam, membuatku yakin bahwa meski aku pergi, aku membawa doa dan restu dari Sambongrejo.
Saat moment penutupan kuliah Kerja Nyata, suasana menjadi lautan air mata. Warga berdatangan di pendopo balaidesa, melambaikan tangan. Anak-anak berteriak memanggil nama kami.
Paginya setelah membersihkan teras posko, aku berpamitan untuk pulang. Aku menoleh ke arah teras, melihat mbahe berdiri dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar melambaikan tangan. “Ati-ati, Le… ojo lali karo Sambongrejo,” ucapnya. Aku pun menjawab, “Matur nuwun, mbah… sampeyan wes dadi wong tuwaku kene.” Air mataku jatuh deras. Aku tahu setelah ini meja ruang tamu akan sepi, tak ada lagi gelas teh hangat untuk kami.
Montorku melaju meninggalkan posko itu. Aku berhenti sekejap tak jauh dari gerbang rumah itu menoleh ke belakang, pemandangan terakhir Sambongrejo perlahan menghilang. Masjid tempatku azan, sekolah tempatku mengajar, jalanan berdebu, rumah sederhana dengan teras luas, dan senyum Mbahe—semua tersimpan dalam hatiku. 45 hari di Sambongrejo mungkin singkat, tapi kenangannya akan abadi. Aku belajar arti pengabdian, cinta, kehilangan, dan pulang. Aku belajar bahwa kadang, sebuah desa kecil bisa menjadi rumah kedua yang tak akan pernah bisa benar-benar kutinggalkan.
Dan setiap kali aku merindukan Sambongrejo, aku hanya perlu memejamkan mata, membayangkan suara azan subuhku menggema di udara dingin desa, suara lembut Bapak Huda yang mengingatkanku pada ayah, dan teh hangat buatan Mbahe yang selalu siap di meja. Semua itu akan selalu hidup di hatiku, selamanya.