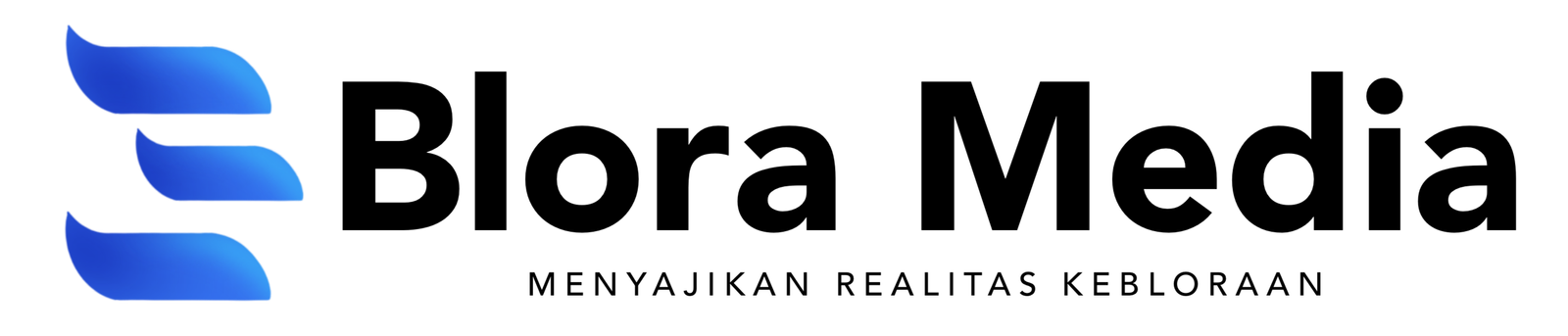Bagi sebagian besar masyarakat luar, nama “Blora” kerap hadir sebagai bayangan buram: tanah tandus, wilayah terpencil, angka kemiskinan yang keras kepala, dan keberagamaan yang kerap dilekatkan pada istilah “abangan.” Stigma itu barangkali tak salah sepenuhnya, tapi juga jauh dari cukup. Karena Blora, seperti hutan jatinya yang tampak sunyi dari luar, menyimpan riwayat panjang perlawanan, kebudayaan, dan peradaban yang tumbuh dalam diam.
Sebagian orang mungkin mengingat Blora karena hutan jatinya yang legendaris atau tambang minyak di Cepu yang dulu sempat disebut sebagai “kota kecil dengan isi perut yang kaya.” Sebagian lain mungkin langsung mengaitkannya dengan ideologi kiri atau nama besar Pramoedya Ananta Toer, sang sastrawan pemberontak yang menjadikan Blora sebagai latar dan inspirasi sejumlah mahakaryanya. Tapi lebih dari itu, Blora adalah sejenis mozaik: semrawut tapi berisi, senyap tapi penuh suara.
Pada 1952, Hans Bague Jassin–kritikus sastra kenamaan yang dijuluki paus sastra Indonesia–menulis pengantar yang getir untuk buku Cerita dari Blora karya Pramoedya. Ia menyebut Blora sebagai “daerah kapur yang miskin” tempat seorang buruh tani hanya bisa hidup dengan 1,5 sen sehari. Potret yang ia lukis bukan sekadar catatan kemiskinan, tapi juga ketangguhan: bagaimana orang tetap hidup, bahkan berkeluarga, di tengah kemelaratan yang menganga. Kalimatnya terasa seperti tangis yang ditulis dengan tinta kesaksian.
Tapi sejarah Blora tidak berhenti pada kegetiran itu. Justru dari rahim kemiskinan dan keterpinggiran, muncul bara-bara kecil yang menolak padam. Salah satunya adalah Pram sendiri, yang lahir dari tanah gersang dan justru menjadikan kekeringan sebagai mata air imajinasi. Melalui cerita-cerita pendek dan novelnya, ia menulis Blora bukan sebagai kota yang dikasihani, melainkan sebagai medan tempur batin, simbol keteguhan, dan ladang perlawanan terhadap penindasan. Ia menulis bukan dari menara gading, tapi dari penjara, pengasingan, dan luka sejarah.
Blora memang tanah yang keras, tapi justru dari kekerasan tanah itulah tumbuh pohon-pohon jati berkualitas dunia. Bukan hanya secara harfiah, tapi juga simbolik. Jati yang kokoh, tak gampang rebah diterpa angin zaman, menjadi metafora paling cocok untuk menyebut masyarakat Blora yang mampu bertahan di tengah keterbatasan. Bahkan dalam sejarahnya, masyarakat Blora sudah menunjukkan bentuk perlawanan yang khas terhadap penjajahan: bukan dengan senjata, tapi dengan keheningan.
Perlawanan diam itu salah satunya dijelmakan dalam sosok Samin Surosentiko, atau Raden Kohar. Alih-alih memilih jalan bangsawan, ia turun ke lapisan rakyat, hidup sederhana, menolak membayar pajak kepada pemerintah kolonial, dan mengajarkan jalan hidup yang lurus dalam arti sebenar-benarnya. Ia tidak membakar gudang, tidak menyerang benteng, tapi mengubah cara hidup: tidak mencuri, tidak menipu, tidak serakah. Itu saja. Tapi itu cukup mengusik kekuasaan, cukup membuat Belanda gelisah. Gerakannya kemudian dikenal sebagai Saminisme, dan para pengikutnya hingga hari ini masih hidup tenang di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo.
Kaum Samin barangkali terlihat “nyeleneh” bagi sebagian orang modern. Tapi jika diperhatikan lebih dalam, mereka adalah cermin kejujuran yang nyaris punah di zaman serba cepat dan gemerlap ini. Hidup dalam kesederhanaan, bekerja dengan tangan sendiri, dan menjaga adat istiadat seperti pusaka. Desa mereka kini menjadi semacam laboratorium hidup tentang bagaimana spiritualitas, kejujuran, dan kebudayaan bisa berjalan berdampingan dalam dunia yang makin keras.
Seperti Kampung Amish di Amerika atau suku Badui di Banten, Kampung Samin Blora adalah tempat di mana waktu berjalan lebih lambat, tapi makna hidup terasa lebih padat. Kita bisa bercengkerama dengan mereka, menikmati kuliner tradisional, menyaksikan kesenian lokal, dan merasakan aura spiritualitas yang membumi, tidak bising tapi menggugah.
Namun Blora tidak hanya dikenal karena Pram dan Samin. Dalam sejarahnya yang panjang, kota kecil ini telah melahirkan banyak tokoh penting yang berkiprah di panggung nasional dan internasional. Ada Oeripan Notohamidjojo, rektor pertama Universitas Kristen Satya Wacana; ada Mochamad Adnan, ahli pertanian lulusan Amerika yang pernah menjadi rektor UGM; dan tentu saja Abdul Mukti Ali, tokoh pembaru pemikiran Islam dan Menteri Agama di era awal Orde Baru.
Belum lagi nama-nama besar lainnya seperti L.B. Moerdani, jenderal legendaris; Ali Murtopo, tokoh intelijen Orde Baru; Marco Kartodikromo, jurnalis radikal era kolonial; hingga para kiai karismatik dan aktivis lintas bidang yang terus bermunculan hingga kini. Blora, ternyata, tak pernah benar-benar kering. Ia justru seperti akar jati: makin tertindas makin menghujam dalam.
Yang menarik, Blora meski secara geografis terpencil, justru menghasilkan masyarakat yang terbuka. Keberagaman agama, budaya, dan pandangan hidup hidup berdampingan tanpa harus diseragamkan. Di satu sisi ada pesantren dan tarekat, di sisi lain ada tradisi abangan dan nilai-nilai lokal yang khas. Semua berjalan dengan ritmenya masing-masing, kadang tabrakan, tapi tidak saling meniadakan.
Kini Blora terus berbenah. Anak-anak mudanya mulai menulis, menggambar, menyanyi, bertani dengan cara baru, dan memperkenalkan wajah Blora yang lebih segar ke dunia luar. Tapi mereka tidak lupa akar. Di balik setiap inovasi, masih ada jejak jati tua, jejak Pram yang menulis dengan nyala hati, jejak Samin yang mengajarkan hidup tanpa kebohongan.
Blora bukan sekadar nama dalam peta. Ia adalah fragmen dari Indonesia yang kadang dilupakan, tapi justru dari situlah ia tumbuh: dari sepi, dari pinggir, dari tanah kapur yang keras kepala. Dan seperti jati, ia tidak tumbuh cepat, tapi ketika tumbuh, ia kokoh. Blora adalah pelajaran bahwa tempat yang tampak miskin bisa sangat kaya. Bukan karena apa yang dipamerkan, tapi karena apa yang disimpan dalam diam.