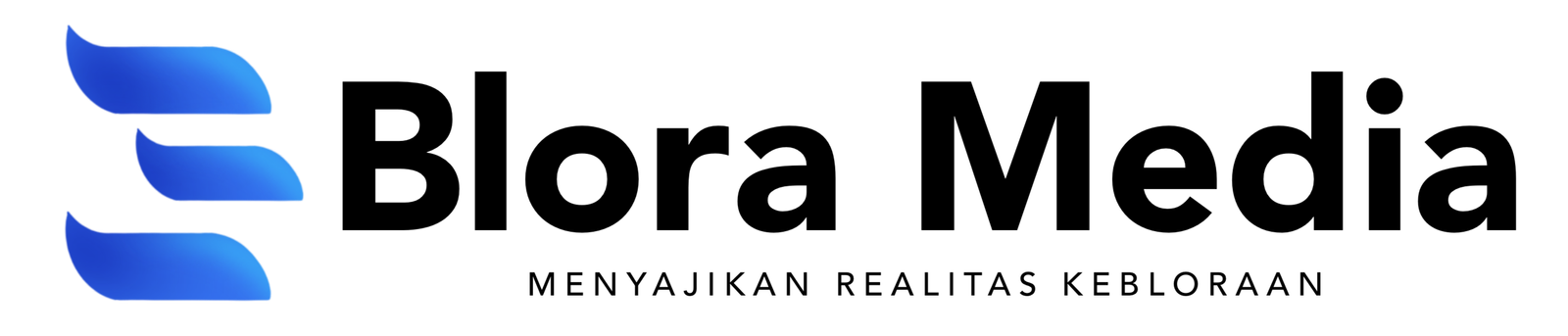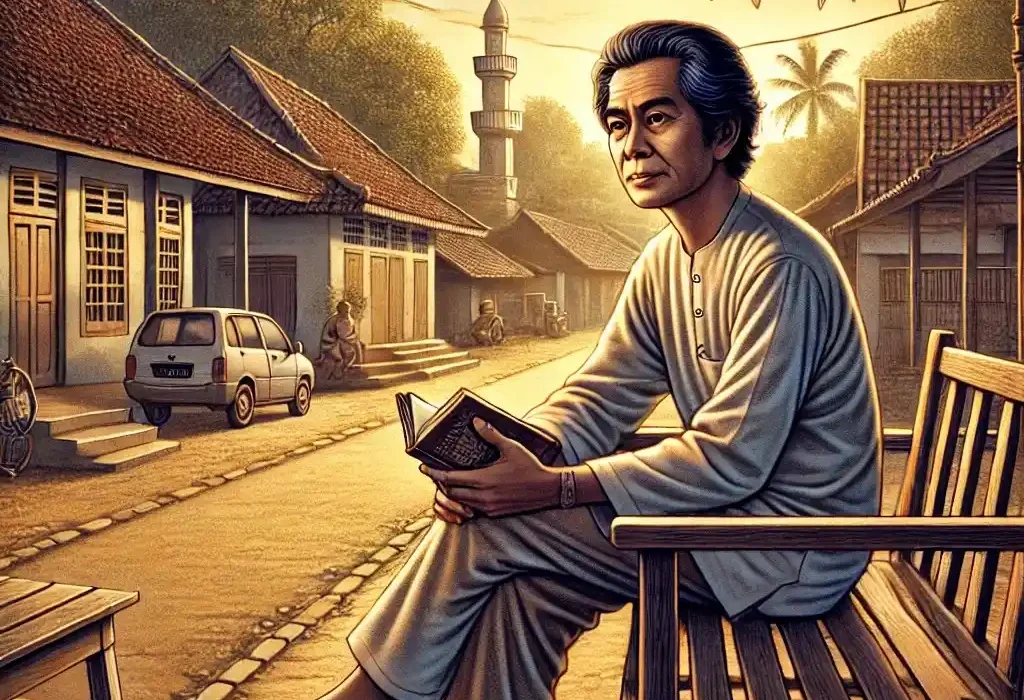Roman karya Pramoedya Ananta Toer yang berjudul Bukan Pasar Malam pertama kali diterbitkan Balai Pustaka pada tahun 1951, itu jauh sebelum Pram ditangkap dan diasingkan Orde Baru ke Pulau Buru. Pada sekitaran tahun itu, berbeda dari novel-novel Pram lainnya yang bercerita tentang gejolak revolusi seperti Perburuan, Keluarga Gerilya atau Percikan Revolusi + Subuh, novel Bukan Pasar Malam malah menceritakan segmen revolusi dari sudut pandang yang lain, yaitu kisah seorang anak yang pulang dari Jakarta untuk menengok ayahnya yang sakit karena penderitaan perang kemerdekaan. Tebal novel ini ± 104 halaman, namun penuh dengan ketegangan dan dialog-dialog pilu yang dialami tokoh dalam isi cerita. Ada kegetiran yang menggigit saat awal membaca cerita dari novel ini. Tak heran bila Romo Y.B Mangunwijaya menyebut jika roman Bukan Pasar Malam merupakan salah satu novel terbaik Pramoedya Ananta Toer yang paling disukainya.
Dikisahkan, Pram baru saja dibebaskan dari penjara setelah tertangkap Belanda di masa revolusi. Setelah bebas ia bekerja di sebuah surat kabar dan menulis buku. Diceritakan ia sudah lama tak bertemu kerabat dan keluarganya yang berada di kampung masa kecilnya karena perang yang melanda. Saat itu Pram sudah menikah dengan istrinya di Jakarta dan keduanya masih menjadi pengantin baru saat sebuah surat datang dengan isi yang menyayat hati. Surat itu dikirim dari Blora dan menceritakan sakit ayahnya yang semakin memburuk. Ayahnya–adalah seorang nasionalis sejati–begitu ungkap Pram dalam ceritanya. Seumur hidupnya ia baktikan untuk mengabdi kepada negara dengan menjadi guru sampai akhirnya menjadi seorang pembesar di sekolah Boedi Oetomo Blora. Rupanya ayahnya juga berkorban selama revolusi berlangsung, ia tertangkap tentara Belanda di Ngawen dan ketika pulang kesehatannya semakin mengkhawatirkan. Barulah di dalam surat dijelaskan bahwa ayahnya menderita TBC setelah perawatan panjang selama tiga bulan. Untuk itulah Pram mencari cara agar bisa pulang kampung ke Blora, menengok ayahnya yang sakit dan sedang menunggu kepulangan anak sulungnya itu.
Roman ini sebetulnya berlangsung hanya dalam satu perjalanan. Namun setiap segmen yang disusun selalu mengungkap kisah-kisah yang dialami keluarga Pram dari mulai masa kejayaan sampai dengan jatuhnya keluarga mereka dalam guncangan revolusi. Agar bisa pulang ke Blora, Pram harus bersusah payah mencari utangan. Dari sana muncul satu gugatan yang mewakili gambaran hatinya ketika melewati Istana Presiden, ia melihat betapa bahagianya orang-orang yang tinggal di dalam istana. Dari sinilah muncul satu kritikan yang menggoyahkan manusia dalam menerima nasib.
–Presiden memang orang praktis–tidak seperti mereka yang memperjuangkan hidupnya di pinggir jalan berhari-harian. Kalau engkau bukan presiden, dan juga bukan menteri, dan engkau ingin mendapat tambahan listrik tigapuluh atau limapuluh watt, engkau harus berani menyogok dua atau tigaratus rupiah. Ini sungguh tidak praktis. Dan kalau isi istana itu mau berangkat ke A atau ke B, semua sudah sedia–pesawat udaranya, mobilnya, rokoknya, dan uangnya. Dan untuk ke Blora ini, aku harus pergi mengedari Jakarta dulu untuk mendapatkan hutang. Sungguh tidak praktis kehidupan semacam itu. (hal 9-10)
Pram pulang ke Blora menaiki kereta api dan di perjalanan ia mengenang semua pertempuran yang terjadi di sepanjang daerah yang dilewatinya. Ia jadi membayangkan bahwa kemerdekaan mengorbankan banyak sekali jiwa manusia yang ingin memperoleh kedamaian hidup. Begitu sampai di Blora, ia disambut oleh adik-adiknya dan keluarga besarnya di kampung. Rumah yang ia tinggalkan bertahun-tahun lalu sekarang ia tempati lagi untuk sementara. Dan terasa perbedaan dari yang dulu dengan masa sekarang; yaitu kemunduran dalam hidup seseorang. Keluarganya tidak seperti dulu lagi, banyak perbedaan dan peristiwa yang membuat nasib saudara-saudaranya sangat menyedihkan. Sejak ibunya yang ia cintai itu meninggal, dan kobaran perang mulai melanda kota kecil itu, tak ada lagi yang mengurus adik-adiknya, mereka semakin kurus dan yang terkecil terus merengek dan menangis. Ayahnya juga hidup dalam pelarian sebelum penangkapan itu terjadi. Sementara Pram harus menerima kenyataan yang lebih pahit lagi, ayahnya kini memang sudah tidak berjuang melawan Belanda, tetapi ia kini terkapar di ranjang melawan TBC yang semakin ganas menyerang tubuhnya yang kurus kering. Dalam kepulangannya yang sebentar itu ia banyak menanggung keluhan dari kerabat dan saudaranya. Mereka bilang bahwa sudah seharusnya rumah masa kecilnya itu diperbaiki, sebab rumah adalah cerminan dari penghuninya itu sendiri, dan dipikirkan pula seluruh biaya perawatan rumah di saat pikirannya semakin kacau dan tak keruan itu.
“Blora ini masih tetap seperti waktu kutinggalkan dulu. Rumah-rumah baru banyak didirikan. Dan rumah-rumah yang dulu sudah miring-miring.” Aku menengok ke arah rumah. Meneruskan, “Dan rumah kami pun sudah begitu rusak.”
…. . “Dan kalau bisa, Gus, kalau bisa –harap rumahmu itu engkau perbaiki. Engkau sudah terlalu lama meninggalkan tempat ini. Dan engkau sudah terlampau lama tak bergaul dengan orang-orang sini. Karena itu, barangkali ada baiknya kuulangi kata-kata orang tua-tua dulu: apabila rumah itu rusak, yang menempatinya pun rusak.” (Hal 43-44)
Pram membawa ayahnya kembali ke rumahsakit saat sakit ayahnya semakin parah, satu-satunya yang selalu dikeluhkan adalah tenggorokannya yang panas, dan ayahnya selalu memekik untuk dibawakan es. Seminggu di perawatan ayahnya sudah merasa jika hidupnya tak akan bertahan lama lagi, hingga ia meminta kepada Pram agar memulangkannya ke rumah, tempat ia bisa berkumpul dan melihat lagi orang-orang terdekatnya berkumpul di sampingnya. Alur cerita novel ini sangat sederhana dengan gaya realisme murni. Di beberapa bagian, terlihat Pram memperlihatkan dialog-dialog permohonan dan permintaan manusia yang kerdil kepada Tuhan yang menunjukkan pantulan aura mistik dan dibalut dengan semangat religiusitas. Sampai pada suatu malam, seorang adiknya menjerit dan mencari-cari keberadaan dirinya yang sedang berada di beranda tengah, saat itulah Pram menyaksikan sendiri maut mencabut nyawa ayah yang dicintainya.
–Tiba-tiba teringat olehku: ayah orang Islam. Dan kembali kudekatkan mulutku pada kupingnya, berseru:
“Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.”
Adikku yang keempat menyela:
“Jangan biarkan terbuka mulut Bapak, Mas.”
Dan kurapatkan dagu ayah ke atas. Tapuk matanya kuturunkan. Di saat itu juga tiada kusangka-sangka para tetangga datang dan memberikan bantuannya. Dagu ayah diikat dengan sepotong kain dikaitkan dengan kepalanya dan kemudian –dengan sendirinya saja–berbareng kami menangis– (hal 90)
Pram kini harus merelakan ayah kebanggaannya, pejuang revolusi yang loyal terhadap para pejuang itu telah pergi meninggalkan dunia tempat para manusia. Dan selama masa perang itu ia telah kehilangan begitu banyak anggota keluarganya. Ia telah kehilangan ibundanya, adiknya yang terkecil, nenek dan kemudian ayahnya yang belum lama menyusul kepergian mereka.
–”Dan di dunia ini, manusia bukan berduyun-duyun lahir di dunia dan berduyun-duyun pula kembali pulang. Seperti dunia dalam pasar malam. Seorang mereka datang dan pergi. Dan yang belum pergi dengan cemas-cemas menunggu saat nyawanya terbang entah ke mana.” –Pramoedya Ananta Toer.